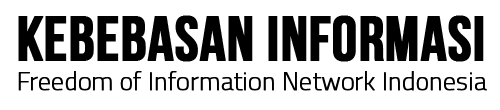Ketika Korupsi Dimulai dari Sekolah
Senin 30/08/2010 – Anak itu sedang memakai baju sekolah ketika ayahnya memberikan uang dua puluh ribu rupiah. Jatah hariannya untuk belanja di sekolah. Saya berdiskusi dengannya untuk belanja apa uang sebanyak itu. Makan nasi goreng atau soto dengan minuman soda. Sisanya untuk mentraktir temannya. Saya mengajaknya berhitung bahwa dalam 25 hari sekolah dia sudah bisa menabung 500 ribu rupiah sebulan. Makanan di sekolah tidak lebih baik dari makanan di rumah. Malas! Kalau di sekolah bisa ramai-ramai. Demikian katanya!
Saya pernah berdiskusi dengan salah satu pemilik sekolah swasta yang cukup terkenal di kalangan atas. Saya bertanya alasan dia mendirikan sekolah mengingat tak ada tanda-tanda dia tertarik atau mencintai suatu proses pendidikan, yang dari sisi ekonomis bukan merupakan bisnis yang menguntungkan. Tak ada orang miskin yang bersekolah di tempat tersebut, karena memang target pasarnya adalah orang kaya. Saya menghitung jumlah uang yang didapatnya dari uang sekolah yang sesungguhnya hanya cukup untuk membayar guru dan karyawan lainnya.
Selain uang sekolah, murid dibebani uang makan yang jumlahnya 125 ribu per bulan atau rata lima ribu rupiah sekali makan. Jumlah yang sangat layak untuk suatu kesederhanaan. Alasan penyediaan makanan tentu agar seluruh murid bisa menikmati hidangan yang sama selama sekolah. Dengan demikian tidak akan terjadi kecemburuan diantara mereka. Artinya karena sekolah menyediakan makan siang, kantin tidak dibutuhkan lagi. Tetapi betapa mengagetkan karena di balik itu semua masih ada bisnis kantin yang sangat besar. Target kami adalah murid yang memiliki uang belanja harian cukup besar. Makanan yang disediakan sekolah hanya untuk memenuhi standar pelayanan dan cukup sederhana karena mereka diharapkan justru makan di kantin sekolah yang berstandar restoran cepat saji. Di kantin semua jenis makanan yang disukai anak muda tersedia, kaya lemak dan kalori yang tentu tidak sehat.
Ketika saya belajar di sekolah dasar, sekolah saya tidak memiliki kantin. Yang ada hanya pelayan sekolah yang kami panggil paman, menyediakan es mambo. Penjualan itu tidak dicampuri oleh sekolah karena hanya dilakukan saat istirahat, betul-betul dilakukan hanya untuk tujuan membantu murid yang haus. Di sekolah lanjutan pertama dan atas, ada kantin sekolah yang diberikan kepada seorang ibu tua. Nampaknya dia juga tidak dibebani pungutan sehingga harga penganannya lebih murah dari di luar sekolah. Selain itu bukan rahasia kalau banyak murid yang justru berutang padanya. Lagi-lagi tentu dengan tujuan sekedar membantu kebutuhan murid yang lapar.
Sejak darma wanita diaktifkan, kantin kemudian lazim harus dikelola istri kepala sekolah bersama organisasinya. Kebutuhan operasional organisasi ibu-ibu itu kemudian dibebankan ke dalam harga makanan. Mereka cukup mencari pemasok makanan, memungut potongan dari harga makanan yang lumayan tinggi. Pengelolanya ibu ketua atau anggotanya cukup membayar komisi ke organisasi. Karena itu jangan heran mengapa harga makanan di sekolah cenderung jauh lebih mahal dibanding di luar sekolah. Pengalaman menguntungkan berbisnis menglola kantin tanpa berkeringat, menyebabkan organisasi ibu-ibu melirik ke bisnis pendidikan lain seperti pengadaan pakaian sekolah, perlengkapan sekolah seperti tas dan buku yang semuanya dibuat atas nama keseragaman. Saya terhenyak ketika menemukan sekolah taman kanak-kanak yang memiliki lima baju seragam yang berbeda setiap hari. Bisnis ini tidak pernah merugikan atau mengalami keterlambatan pembayaran karena berbagai biaya ditagih melalui system sekolah. Tentu tidak ada orang tua yang protes bila tak ingin anaknya mendapat kesulitan.
Merasakan mudahnya mendapatkan keuntungan melalui kebutuhan murid, organisasi ibu-ibu ini kemudian merambah pendidikan tinggi. Semua kebutuhan yang semula tidak ada menjadi diadakan. Di perguruan tinggi darma wanita bersaing dengan koperasi, yang system pengelolaannya ternyata sama hanya memungut selisih harga jual. Para pemasok berlomba untuk menghubungi para istri pimpinan agar bisa mendapat order terutama di setiap awal tahun. Kembali atas nama keseragaman, semua orang tua mahasiswa harus membeli barang yang disediakan atas nama perguruan tinggi. Mahasiswa selalu protes tentang kenaikan SPP, tetapi terpaksa diam dengan berbagai pungutan suka rela yang dilakukan dengan keterpaksaan.
Bisnis lain yang menggiurkan adalah bimbingan belajar. Di masa lampau guru memberi tambahan bimbingan belajar di luar jam sekolah bagi murid yang dianggap kurang. Keadaan ini berkembang pada pelajaran-pelajaran yang dianggap penting. Guru menyediakan bimbingan bagi siapa saja termasuk murid-murid yang sebenarnya cerdas. Tidak semua guru melakukan pemaksaan untuk mengikuti bimbingan. Tetapi murid juga tahu bahwa materi ulangan biasanya diberikan lebih intensif dalam bimbingan belajar. Hasilnya murid-murid menganggap bimbingan belajar jauh lebih penting dari pada proses belajar di sekolah. Guru-guru juga tidak pernah melakukan evaluasi tingkat keberhasilan murid melalui bimbingan belajar atau melalui proses reguler di sekolah.
Jangan mengira bimbingan belajar hanya ada di sekolah dasar dan menengah. Bisnis ini juga merambah pendidikan tinggi. Kembali untuk mata kulaih yang dianggap penting, cukup banyak dosen memberi bimbingan. Proses belajar di bangku kuliah diberikan apa adanya dan bagi mereka yang ingin pendalaman bisa mendapatkannya di luar jam kuliah secara privat. Keinginan untuk mengejar indeks prestasi membuat mahasiswa dengan latarbelakang ekonomi kuat memilih untuk ikut bimbingan belajar dari dosen. Sama seperti uraian sebelumnya, tidak pernah ada evaluasi tingkat keberhasilan proses belajar.
Bisnis pendidikan kemudian berkembang lebih jauh melalui berbagai studi banding. Untuk sekolah dasar dan menengah, murid didampingi orang tua mereka. Guru dan organisasi orang tua bekerja sama dengan travel biro yang biasanya dimiliki oleh salah satu orang tua murid. Hal yang sama juga terjadi di perguruan tinggi. Studi banding tidak cukup dilakukan di dalam negeri tetapi merambah ke luar negeri tanpa alasan yang kuat. Jangan heran kalau kita ke luar negeri, tempat-tempat belanja dipenuhi oleh siswa atau mahasiswa Indonesia yang sedang studi banding. Mereka memang tak punya tujuan khusus studi banding kecuali pesiar.
Bisnis selanjutnya adalah pesta-pesta sekolah seperti perpisahaan. Lazimnya acara perpisahaan seremonial dilakukan secara sederhana di sekolah. Acara yang lebih spesifik ditangani alumni sendiri dengan mengundang guru-guru mereka. Saat ini acara perpisahan dilakukan di hotel atau restoran mewah dengan biaya yang dipungut ke alumni yang baru lulus dan diselenggarakan oleh guru. Murid-murid hanya mengikuti apa kehendak guru mereka dan tidak bisa berkreasi bebas sesuai kebutuhan mereka.
Berbagai cerita di atas hanya menunjukkan pada kita bagaimana ketegaan pengelola pendidikan mencari rejeki dari anak-anak mereka sendiri. Anak-anak yang tidak bisa menolak karena yang melakukan adalah para orang tua mereka yang berprofesi terhormat sebagai pendidik. Orang tua murid atau mahasiswa yang miskin akhirnya menjadi rendah diri tak mampu mengikuti alur yang dibuat untuk menyenangkan guru-guru mereka. Mereka cuma bisa melihat guru atau dosen mereka tanpa rasa hormat. Guru dan dosen menjadi pilih kasih, memberi perhatian lebih bagi mereka yang membeli jualan mereka.
Sudah saatnya para pengelola pendidikan termasuk guru dan dosen kembali ke filosofi pendidikan yaitu mencerdaskan anak didik termasuk kecerdasan mental dan moral. Tak ada gunanya kita mengeluh bagaimana buruknya system pendidikan di Indonesia, tetapi tak pernah sadar bahwa sebagai pendidik kita termasuk yang punya potensi terbesar merusaknya. Tak akan mungkin kita bisa mencapai cita-cita menghasilkan generasi muda yang penuh harapan kalau dalam proses pendidikannya saja mereka sudah melalui system yang penuh potensi penyalah gunaan kekuasaan. Kalau program pendidikan dikelola sebagai pusat kekuasaan untuk memaksakan keinginan, maka tak perlu heran apa yang terjadi di pusat kekuasaan besar lainnya?
Triyatni M, dosen, arsitek, bekerja di Universitas Hasanuddin