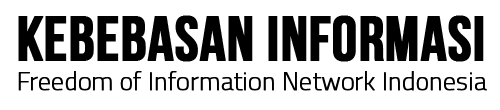Kamis 03/06/2010 – Kehadiran UU KIP patut disambut gembira meski ada beberapa hal yang perlu dipertegas. Di antaranya informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum, dan memberitakan informasi yang tidak seharusnya dibicarakan.
RUANG teater di gedung Compagnietheater Kloveniersburgwal, Amsterdam, Belanda mendadak senyap, ketika Wilf Wangga, wartawan dari Zimbabwe mulai berbicara, Senin (3/5) ini. Laki-laki brewokan itu menceritakan bagaimana dirinya selalu dikejar-kejar pemerintahan Zimbabwe karena berita yang dibuatnya. “Tidak ada kebebasan pers di Negara saya, karena itulah Saya melarikan diri,” katanya.
Cerita Wilf dalam Peringatan hari Kebebasan Pers se-Dunia (World Press Freedom Day) di Amsterdam itu seperti mengingatkan keadaan saat Mantan Presiden (alm) Soeharto berkuasa di Indonesia. Ketika itu masyarakat (termasuk pers) hidup dalam suasana mencekam. Berutung, reformasi 1998 mengubah semuanya. Termasuk dalam dunia informasi yang melahirkan UU Pers, UU Penyiaran dan belakangan, UU KIP.
Kelahiran UU Pers dan UU Penyiaran, seakan-akan menjadi salah satu jaminan kebebasan informasi di Indonesia. Meski masih banyak kelemahan di dalamnya, namun dua UU itu menjadi salah satu sandaran hukum bagi dunia pers di Indonesia untuk bekerja relatif lebih bebas dari sebelumnya. Terlebih lagi, belakangan muncul UU Keterbukaan Informasi Publik yang semakin memperkokoh hal itu.
Secara umum, UU yang terdiri dari 16 bab dan 46 pasal itu mengatur hak dan kewajiban publik dan lembaga publik untuk bisa mendapatkan informasi. Meski terkesan sederhana, namun esensi UU KIP adalah transparansi lembaga publik pada stakeholder-nya, yang tidak lain adalah masyarakat. Begitu berartinya UU ini, hingga Anggota DPR dari Partai Golkar Tantowi Yahya menilai UU ini sebagai masterpiece bagi DPR.
Dalam UU KIP, masyarakat berhak mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan. Bila badan publik itu tidak memberikannya, maka masyarakat diberi hak untuk mengajukan gugatan kepada lembaga yang bersangkutan. Siapa saja yang dimaksud dengan lembaga publik itu? Tak lain adalah semua lembaga yang dikelola oleh pemerintah (termasuk BUMN) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan NGO yang menerima dana dari pemerintah.
Dalam sebuah diskusi, Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan, UU KIP itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Karena itulah, Agus menjadi salah satu pendukung UU KIP dan aktif melakukan kampanye untuk merealisasikan hal itu. “Memang tidak ada alasan untuk menolak UU KIP ini, dan kondisi ini harus terus dijaga,” kata Agus.
Black Hole
Meski diselimuti dengan atmosfir kebebasan informasi dan harapan terciptanya kondisi yang lebih transparan, namun UU KIP juga menyimpan lubang hitam yang bertentangan dengan semangat transparansi itu. Lihat saja Bab V UU KIP, khususnya pasal 17 yang justru memberi ruang pada ketertutupan. Dijelaskan, dalam pasal itu, semua informasi yang dibutuhkan publik bisa diberikan, kecuali informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum.
Termasuk menghambat proses penyidikan tindak pidana, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Juga mengungkapkan data intejen kriminal dan beberapa pengecualian lainnya. Tantowi Yahya mencium bau tidak “sedap” dalam pasal ini. Meski, pergumulan politik di DPR tidak mampu membuatnya berhasil mengubah pasal ini. “Jangan sampai objek bersembunyi di balik itu. Walaupun itu ditegaskan untuk informasi terkecualikan,” katanya.
Muncul spekulasi, hadirnya pasal 17 ini adalah sebuah sikap politik pemerintah, untuk tidak sepenuhnya menginginkan transparansi. Hal itu bisa dilihat dari perjalanan pembuatan UU KIP yang dibayang-bayangi dengan UU Rahasia Negara yang isinya justru mendegradasi UU KIP. Penentuan obyek yang secara hukum yang terikat dengan UU ini menjadi
Transparansi setengah hati itu terlihat dalam pergulatan menentukan obyek hukum UU KIP. Ada satu poin yang perlu dibahas selama enam bulan. Yakni menyangkut status BUMN yang merupakan badan publik atau tidak. “Badan publik hanya yang dapat dana dari APBN dan APBD. Pemerintah mengatakan BUMN masuk rezim UU BUMN, akhirnya disepakati BUMN adalah badan publik juga,” ungkap Mantan Ketua Panja KIP Arief Mudatsir Mandan.
Reaksi Mabes TNI dalam “menyambut” hadirnya UU KIP ini juga menunjukkan adanya sikap tidak sepenuhnya menerima transparansi. Deputi VII bidang Komunikasi dan Info, Kemenko Polhukam yang juga mantan Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen mengatakan, TNI tidak akan memberikan informasi kepada publik mengenai kedaulautan negara, kekuatan pertahanan dan kekuatan wilayah perbatasan.
Bahkan, Sagom mengatakan TNI bisa menuntut media massa yang memberitakan informasi yang tidak seharusnya dibicarakan. Termasuk bila ada pejabat negara atau dari unsur TNI yang membocorkan rahasia negara. “Orang itu yang akan masuk penjara, diproses hukum karena mengatakan hal yang dilarang. Kecuali berdasar dokumen yang sudah lama beredar, itu hak pengutip,” ujarnya seperti dikutip Koran Jakarta.
Freedom of Information Act
Reaksi Sagom seakan membenarkan analisa jurnalis Andreas Harsono yang pesimistis dengan pelaksanaan UU KIP. Andreas justru mempertanyaan kemauan TNI (yang notabene merupakan lembaga publik) untuk mengubah budaya ketertutupan yang selama ini dilakukan. Dalam kasus penculikan aktivis yang dilakukan Tim Mawar Kopassus, misalnya. Andreas mencatat, dari 11 orang Kopassus yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer Jakarta, hanya satu orang yang benar-benar dipecat dari Kopassus.
“Bagaimana kita bisa mendapatkan dokumen hukum dari pengadilan tinggi militer Jakarta? Lembaga Imparsial dan Kontras sudah minta dokumen-dokumen ini selama tiga tahun, dan tak berhasil,” katanya kepada Jurnal Parlemen.com. Begitu juga dalam kasus pembunuhan aktivis Papua, Theys Eluay yang melibatkan tujuh perwira. Hanya satu orang yang mundur dari Kopassus. Sisanya masih aktif bekerja.
“Juga kasus pembunuhan Munir, seberapa jauh kita bisa minta dokumen-dokumen BIN tentang notulensi rapat, nota-nota pembayaran dari dalam tubuh BIN?” katanya. Pemrakarsa genre jurnalisme sastrawi ini membandingkan dengan kondisi di AS yang memiliki Freedom of Information Act. Dengan UU itu, Andreas berhasil meminta State Department AS data-data pembunuhan anggota PKI pada 1965-1966. Juga peristiwa pembunuhan tiga guru Freeport di Mile 62-63, Timika, Papua.
Di Washington D.C, lewat kantor FARA (Foreign Agent Registration Act), Andreas bahkan mengaku bisa mendapatkan data tentang aksi agen Badan Intelijen Negara (BIN) yang membayar Collins & Co, untuk melobby Capitol Hill. Lengkap hingga bayaran per-bulan.
“Saya juga bisa dapat nota sewa pesawat jet pribadi yang dipakai Senator Bob Dole guna lobby di New York untuk kepentingan Yohanes Hardian Widjonarko, orang kepercayaan Taufik Kiemas, dalam melobby Capitol Hill, saya bisa tahu berapa (biaya)mereka makan siang, atau berapa duit mereka terima dari Yohanes Hardian dan BIN,” tegas Andreas. Yohanes Hardian adalah orang yang membayari rekening telepon Muchdi, seperti terungkap dalam pengadilan pembunuhan Munir.***
(Iman Dwi Nugroho)
Laporan: Samsul Muaarif, Nofellisa, Yayat R. Cipasang dan Iman Dwi Nugroho