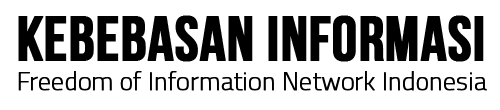Ahmad Alamsyah Saragih
Dalam konteks tertentu, kendati informasi yang diminta adalah informasi yang terbuka, kehati-hatian dalam memenuhi hak atas informasi diperlukan. Hal ini merupakan bagian dari akuntabilitas sosial dalam pelayanan informasi. Teknis penyampaian suatu informasi terbuka di daerah yang tengah mengalami ketegangan sosial yang tinggi akan berbeda dengan daerah yang tidak berada daam kondisi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis tertentu, suatu informasi yang secara yuridis bersifat terbuka memerlukan pilihan teknis penyampaian yang khusus tanpa meniadakan hak untuk mengetahui.
Bagian ini akan memuat tahapan analisis dalam pemberian informasi yang terbuka namun diduga memiliki risiko berdasarkan aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (5) UU KIP. Namun demikian tidak semua informasi terbuka harus mendapatkan perlakuan ini. Paling tidak ada tiga tahapan yang perlu dilakukan untuk menentukan teknis penyampaian kepada publik atau kepada pemohon.
Tahap-1: Mengidentifikasi Informasi Sensitif
Pelayanan informasi merupakan suatu aktifitas yang tidak luput dari risiko terkait aspek sosial, politik, ekonomi, budaya maupun aspek pertahanan dan keamanan negara. Derajat risiko terhadap berbagai aspek tersebut secara yuridis sebagian telah diantisipasi melalui skema informasi yang dikecualikan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu suatu informasi yang secara yuridis terbuka tetap memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap kemungkinan penyimpangan (abuse) yang berdampak merugikan terkait berbagai aspek tersebut.
Badan Publik perlu mengidentifikasi berbagai informasi terbuka yang memiliki risiko tinggi. Melalui identifikasi akan dihasilkan daftar informasi terbuka yang bersifat sensitif. Informasi inilah yang menjadi objek utama untuk dianalisis dan dilengkapi dengan pertimbangan secara tertulis untuk diterapkan kebijakan khusus dalam pemberian informasi.
Tahap-2: Menganalisis Risiko
Tahap berikutnya, setelah identifikasi informasi terbuka yang bersifat sensitif, adalah analisis risiko yang mungkin terjadi dari pemberian informasi publik tersebut. Dalam tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai kemungkinan penyimpangan jika informasi diberikan. Kemungkinan tersebut dapat berupa pengalaman maupun prediksi. Risiko tidak bersifat statis, namun berkembang sesuai dengan situasi sosial dan kesiapan personal di Badan Publik.
Dalam banyak hal informasi yang bersifat terbuka sebagaimana diatur oleh Undang-undang tidak memiliki risiko berarti, namun dalam kondisi sosial-politik tertentu risiko tersebut cukup berarti. Sebagai contoh:
Kasus-1:
BPK mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan yang telah diserahkan ke DPR secara lengkap melalui situs mereka. Setiap orang dapat mengakses informasi tersebut dengan cara mngunduhnya tanpa perlu memberikan identitas terlebih dahulu. Namun demikian, dalam perkembangan informasi tersebut sering disalahgunakan dengan cara mengutip temuan yang telah dimanipulasi.
Penyimpangan ini kerap terjadi di wilayah-wilayah yang sedang menyelenggarakan Pilkada dimana kandidat incumbent merupakan salah satu peserta pemilihan. Ini adalah salah satu bentuk risiko secara politik yang perlu dianalisis untuk menentukan teknis penyampaian LHP ke publik, namun bukan berarti dapat dijadikan alasan untuk mengubah status LHP menjadi dokumen yang tertutup.
Kasus-2:
Beberapa Badan Publik sering menghadapi permintaan salinan dokumen kontrak dengan pihak ketiga yang menjadi pemenang lelang, tidak termasuk lampiran pendukungnya. Secara yuridis, setelah dilakukan pengaburan terhadap identitas dan alamat personal yang mewakili perusahaan pemenang lelang, dokumen tersebut bersifat terbuka.
Namun demikian, salah satu Badan Publik pernah mengalami persoalan serius terkait penyalahgunaan dokumen tersebut sebelum UU KIP diberlakukan. Dokumen tersebut digandakan dengan memanipulasi identitas perusahaan pemenang lelang dan alamat lengkapnya, kemudian digunakan oleh pihak tertentu untuk mengikuti proses prakualifikasi suatu lelang di instansi pemerintah.
Penyimpangan ini secara ekonomis berisiko merugikan negara dan para peserta lelang yang mengikuti proses prakualifikasi secara jujur. Akan tetapi risiko tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah status informasi yang terbuka menjadi informasi yang tertutup atau dikecualikan.
Diperlukan prioritas dalam mendalami risiko. Agar prediksi dapat lebih akurat tidak jarang dilakukan pendalaman terhadap pihak-pihak pemanfaat informasi melalui untuk mendalami polapola penyimpangan yang mungkin terjadi. Tentunya tidak mungkin melakukan hal ini terhadap semua jenis informasi terbuka yang dikuasai oleh Badan Publik. Pendalaman dilakukan terhadap jenis informasi terbuka yang diduga memiliki risiko (informasi publik yang sensitif) untuk konteks tertentu.
Selain mengidentifikasi pola penyimpangan, juga perlu dianalisis faktor penyebab maupun faktor yang mendukung atau faktor-faktor yang mempermudah terjadinya penyimpangan terkait dengan aspek materi maupun prosedur pelayanan. Hasil identifikasi ini akan menjadi bahan untuk menyusun suatu rekomendasi teknis penyediaan informasi kepada pemohon.
Tahap-3: Menyusun Rekomendasi
Tahap terakhir adalah menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis risiko. Rekomendasi dapat mencakup hal-hal teknis yang berkaitan dengan materi (terkait format informasi yang diberikan) maupun prosedur (terkait tata cara pemberian informasi). Hasil dari rekomendasi boleh jadi merupakan masukan untuk perbaikan SOP layanan informasi. Namun demikian, rekomendasi tidak boleh berupa keputusan untuk menutup informasi. Sebagai contoh:
Kasus-1 (lanjutan):
Setelah mencermati gejala penyalahgunaan informasi lengkap LHP BPK yang diumumkan melalui situs lembaga ini, akhirnya BPK mengubah kebijakan: (i) dari sisi materi, publikasi proaktif melalui situs diubah formatnya menjadi format ringkasan LHP; (ii) secara prosedural, informasi lengkap LHP BPK diubah pola penyediaannya dari semula bersifat proaktif menjadi pasif, sehingga termasuk dalam kategori informasi tersedia setiap saat. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui email atau datang langsung.
Dengan demikian identitas pemohon dapat tercatat oleh BPK. Selain itu, dalam formulir pemberian informasi ditulis peringatan bahwa penyalahgunaan informasi ini dapat dituntut secara hukum. Perubahan kebijakan ini tidak mengubah status informasi lengkap LHP BPK menjadi informasi tertutup, namun hanya berubah dalam hal prosedur layanan, karena secara yuridis informasi tersebut adalah informasi terbuka.
Kasus-2 (lanjutan):
Untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan salinan dokumen kontrak dengan pihak ketiga, setelah melakukan analisis risiko, PPID dapat merekomendasikan perbaikan kebijakan yang menyangkut dua kemungkinan berikut: pertama, dari sisi materi, penanganan secara konvensional dapat dilakukan dengan mengubah format salinan kontrak menjadi ringkasan kontrak yang berisikan informasi-informasi penting agar tujuan pemohon tetap dapat terpenuhi.
Format baru tersebut dilegalisir oleh Badan Publik. Jika teknologi memungkinkan, dapat dilakukan watermarking pada salinan dokumen sedemikian rupa sehingga manipulasi sangat sulit dilakukan. Alternatif yang lebih canggih, dengan penyediaan file elektronik yang tidak mungkin dicetak dan diedit;
Kedua, dari sisi prosedur, untuk meyakinkan pemohon bahwa format ringkasan telah sesuai dengan tujuannya, maka disediakan fasilitas untuk menyaksikan salinan asli yang telah dilakukan pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan yang ada di dalamnya. Cara ini untuk memberikan kesempatan bagi Pemohon mengusulkan tambahan informasi penting lain untuk dimuat dalam ringkasan agar tujuan permohonan tetap tercapai.
Analisis terhadap informasi sensitif tidak menghasilkan rekomendasi untuk menutup informasi yang secara yuridis bersifat terbuka. Namun analisis ini akan menghasilkan suatu teknis penyampaian informasi sebagai pemenuhan hak warga negara untuk mengetahui. Secara umum pemenuhan hak untuk mengetahui ini memiliki gradasi sesuai tingkat risiko (Diagram-2.1):
- Mendapatkan salinan sesuai aslinya.
- Mendapatkan salinan dengan format berbeda.
- Menyaksikan dengan mencatat.
- Menyaksikan tanpa mencatat.
Secara empirik, untuk kasus penyaksian telah pernah diputus oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Dalam putusannya Komisi Informasi Jawa Timur telah memutuskan bahwa ‘Dokumen Kontrak’ beserta dokumen pendukunganya pada seluruh kegiatan dan pekerjaan di Tahun Anggaran (TA) 2010 sampai dengan (s.d) TA 2012, dan SPJ beserta dokumen/bukti pendukungnya pada perjalanan dinas TA. 2010 s.d TA 2011 adalah dokumen terbuka setelah pemohon mengaburkan informasi yang dikecualikan yang ada di dalamnya. Namun untuk amar putusan, Majelis Komisioner hanya memerintahkan Termohon untuk ‘menunjukkan dan memperlihatkan’ seluruh data dan informasi tersebut kepada Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan tersebut diterima,[1] bukan memberikan salinan.
Diagram-2.1. Memperlakukan Informasi Publik Yang Sensitif
Dalam jangka panjang, kewajiban menyusun pertimbangan tertulis untuk setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik akan berdampak positif. Inilah cara untuk mendorong perbaikan teknis dalam pelayanan informasi di Badan Publik di satu sisi, dan akuntabilitas sosial pelayanan informasi di sisi lain. Rekomendasi teknis berikut hasil analisis di atas dapat menjadi masukan untuk perubahan SOP penyediaan informasi yang bersifat terbuka tersebut. Akan tetapi tidak untuk mengubah status informasi informasi tersebut menjadi tertutup.
Keterbukaan Informasi dan Paradoks Akuntabilitas
Tata pemerintahan yang demokratis niscaya mensyaratkan akuntabilitas untuk kelangsungan sistem pemerintahan yang efektif dan kepercayaan publik sekaligus. Membangun sistem akuntabiltas dalam banyak hal dipandang sebagai suatu keharusan agar sistem pemerintahan dapat terhindar dari korupsi, nepotisme dan diskresi yang merugikan publik terkait tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Tarik menarik antara akuntabilitas yang bertujuan agar penyimpangan dapat dibatasi di satu sisi dengan kebutuhan untuk berperilaku inovatif dalam pengambilan keputusan di sisi lain, telah melahirkan suatu trade-off yang disebut sebagai ‘paradoks akuntabilitas’ (Jos and Tompkins, 2004).[2]
Sistem akuntabilitas pada dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi berbagai penyimpangan tersebut, namun secara alamiah juga dapat mengurangi indepedensi dan diskresi dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam mengatasi situasi yang khusus. Tanpa transparansi, kecenderungan tersebut berpeluang untuk tak terlihat dan memperburuk keadaan.
Kendati demikian transparansi di sisi lain dirasakan sebagai suatu ancaman bagi pola-pola pengambilan keputusan yang konvensional akibat meningkatnya risiko (Anechiarico and Jacobs, 1996).[3] Pengawasan yang berlebihan selain menambah biaya juga merusak sifat responsif suatu kerja-kerja administratif terhadap publik yang dilayani (Fesler and Kettl, 1991).[4] Pengawasan yang begitu ketat akan melahirkan barisan pelayan publik yang lebih piawai dalam mengelola akuntabilitas administratif daripada memutuskan suatu pilihan skema layanan yang tepat sesuai situasi dan kebutuhan publik.
Untuk menjalankan suatu layanan yang responsif pada wilayah-wilayah situasi sosial yang beragam dan lebih kompleks diperlukan inovasi, sementara inovasi mengandung risiko. Otoritas publik dengan tingkat akuntabilitas yang begitu tinggi akhirnya ditandai dengan karakter inovasi dan fleksibilitas yang rendah (Radin, 2006).[5] Pada organisasi-organisasi tersebut perhatian lebih tertuju pada upaya untuk mencermati upaya menghindari kesalahan administratif daripada keberhasilan dalam memecahkan masalah layanan secara langsung.
Pelayanan informasi publik kini telah menjadi kewajiban yang berlaku bagi semua Badan Publik. Selama ini fungsi pelayanan selalu terkait dengan tugas spesifik dari Badan Publik tersebut. Agar tidak terjadi konflik prioritas berkepanjangan, UU KIP telah mewajibkan Badan Publik menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab mengelola informasi dan dokumentasi di Badan Publik. UU KIP sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dalam praktik, PPID akan berhadapan dengan tiga kondisi memaksa yang kerap menyulitkan di luar persoalan-persoalan cara pandang. Pertama adalah akses informasi internal yang terkendala oleh manajemen dokumen yang buruk di internal Badan Publik. Kedua, Pemohon informasi yang telah dijamin haknya untuk dilayanai sesuai skema dan batasan waktu yang telah ditetapkan oleh UU KIP (10 hari kerja) untuk informasi berdasarkan permintaan dan 6 bulan sekali untuk memutakhirkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala (proactive disclosure). Ketiga, tekanan pertanggungjawaban administratif dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan utama (core business) atau tugas-tugas rutin dari Badan Publik tersebut.
Ketebukaan informasi dalam kondisi di atas kerap menyebabkan perasaan terancam akibat terbukanya berbagai dokumen yang selama ini dianggap tertutup sehingga dirasakan mengganggu zona nyaman para pelaku di internal Badan Publik tersebut, baik negara maupun non negara. Hal ini lazim terjadi untuk suatu perubahan. Apa lagi dalam UU KIP, pelayanan informasi oleh Badan Publik wajib dilaksanakan dengan prinsip mudah, cepat, dan berbiaya ringan. Untuk itu UU KIP telah mengatur mekanisme keberatan internal kepada atasan PPID dan jika juga tidak direspon atau ditolak, masyarakat pemohon informasi dapat mendaftarkan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.
Dalam perkembangan ketiga hal di atas, akhirnya terjadi konflik prioritas yang cenderung berakhir dengan pilihan untuk mengabaikan permohonan informasi. Kebanyakan Pejabat Publik terpaka lebih peduli dengan pengamanan tanggung jawab administratif daripada mengoptimalkan pelayanan yang diwajibkan ketika dinilai berisiko. Situasi seperti inilah yang dimaksud sebagai ‘paradoks akuntabilitas’ administratif. Dalam intensitas tertentu akuntabilitas administratif telah menyebabkan inovasi atau hal-hal baru yang dianggap berisiko menemukan disinsentifnya.
Dalam layanan informasi, jalan keluar dari perangkap paradoks akuntabilitas tersebut,diantaranya adalah dengan mengenalkan teknik-teknik penyampaian informasi yang relatif aman dan mampu menjawab kecemasan tersebut. Salah satunya adalah menerapkan penanganan informasi sensitif sebagaimana telah diuraikan di atas.
———-
[1] Lihat Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 119/ VII/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012, par. [6.2], [6.3] dan [6.4], antara: Moh. Sidiq vs Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.
[2] Jos, P.H. and Tompkins, M.E. ‘The Accountability Paradox in an Age of Reinvention’, dalam Administration & Society, 36(3), 2004, hal. 255-281.
[3] Anechiarico, F. and Jacobs, J. The Pursuit of Absolute Integrity: How Corruption Control Makes Government Ineffective. Chicago: University of Chicago Press, 1996, hal. 174–176.
[4] Fesler, J.W & Kettl, D.F. The Politics of the Administrative Process. New Jersey: Chatham House Publishers, 1991, hal. 321.
[5] Radin, B.A. Challenging the Performance Movement: Accountability, Complexity and Democratic Values. Washington: Georgetown University Press, 2006, hal. 44–45.