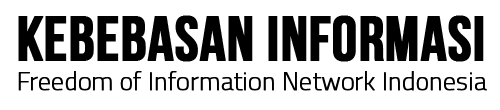oleh muhammad mukhlisin | Des 10, 2014 | Editorial
Hari ini, 9 Desember 2014, diperingati sebagai hari anti korupsi dunia. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo direncanakan akan menghadiri perayaan hari anti korupsi sedunia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Yogjakarta 9-11 Desember 2014. Momentum hari anti korupsi seharusnya dimanfaatkan untuk berbenah dan mengevaluasi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Secara terminologi, korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” dari kata kerja “corrumpere” = busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Sementara itu, Transparency International mendefinisikan korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Korupsi memang identik dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Namun budaya korupsi bisa saja menjadi virus di semua lapisan masyarakat. Seorang bos perusahaan bisa saja melakukan tindakan korupsi dengan memangkas gaji karyawannya. Seorang guru di sekolah yang menelantarkan siswanya. Bahkan siswa yang menyontek pun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
Menarik untuk menyelisik hasil penelitian Transparansi International Indonesia (TII) tentang integritas dan anti korupsi kaum muda yang diluncurkan 2013 lalu. Hampir semua responden tidak menyetujui tindakan korupsi. Namun di sisi lain mereka permisif terhadap tindakan korupsi terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, 15-20% pemuda memilih untuk tidak melakukan pengaduan jika terjadi tindakan korupsi.
Ketika ditanyakan apakah responden siap melaporkan atau membuat pengaduan jika dihadapkan dengan perilaku korupsi, seperti guru yang meminta imbalan uang jika hendak lulus ujian, maka lebih dari 40% responden rural dan urban memilih akan melakukan pengaduan jika hal itu terjadi, sementara mereka yang mengaku sudah pernah melakukannya kurang dari 10%.
Dari penelitian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa di tengah masyarakat kita orang yang peduli terhadap anti korupsi secara pasif banyak jumlahnya. Namun timbul dilema keengganan untuk menjadi pejuang anti korupsi secara aktif. Keengganan untuk melaporkan tindakan korupsi bisa jadi disebabkan karena kekhawatiran akan keselamatan pelapor atau alasan lain.
Dalam penelitian lain, TII juga mengungkapkan fakta bahwa tingkat korupsi birokrasi dan korupsi politik masih tinggi di Indonesia. Dalam indeks persepsi korupsi, Indonesia menduduki peringkat 107 dari 175 negara. Indeks korupsi Indonesia jauh tertinggal dibanding negara tetangga, Malaysia. Negeri Melayu tersebut menduduki peringkat 50 dengan skor 52. Sementara itu, Filipina dan Sri Lanka menduduki peringkat 82 dengan skor 38. Selanjutnya, Singapura, berada di level 7 dengan 84 poin.
Negara kita masih mempunyai tugas berat dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Perlu kebijakan dari hulu ke hilir untuk memberantas korupsi yang semakin hari semakin kompleks modus pelaksanaannya.
Selain itu, penting juga melakukan penanaman integritas dan transparansi terhadap semua lapisan masyarakat. Hal tersebut senada dengan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dirancang oleh KPK. Dalam strategi pencegahan korupsi penekanan yang penting adalah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini penting karena dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas maka responsibilitas pegawai negara akan ditingkatkan.
Beruntung Indonesia sudah mempunyai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbuka. UU KIP merupakan sarana bagi masyarakat untuk melakukan kontrol dan feed back terhadap kinerja pemerintah.
Tentu perjalanan implementasi UU KIP ini bisa dibilang merangkak. Perlu waktu untuk melakukan pembenahan sehingga implementasinya bisa dijalankan sempurna. Mari bersama-sama memanfaatkan UU KIP.

oleh Parliamentary Center | Agu 18, 2014 | Editorial
Hasil uji akses Indonesian Parliamentary Center (IPC) membuka mata publik terhadap KPU, betapa pelayanan informasi publik di lembaga penyelenggara pemilu ini, masih di bawah standar UU Keterbukaan Informasi Publik. Dari 40 permintaan informasi, hanya 7 permohonan yang dilayani. 7 Permohonan tersebut diajukan melalui surat dan permohonan secara lisan (langsung).
Pembelajaran dari proses ini adalah: 1. Ada dua sarana permohonan yang potensial diabaikan oleh KPU, yaitu permintaan via fax dan email. 2. Ada dua jenis informasi yang potensial diabaikan, yaitu permohonan informasi anggaran dan logistik. Tentu ini ironis, mengingat informasi anggaran dan logistik merupakan informasi publik yang wajib dibuka. Sementara cara permintaan informasi dengan email dan fax pun, sama-sama dijamin UU, apalagi KPU memampangnya di situs mereka.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU RI, hingga hari ini belum juga terbentuk. Padahal, Pejabat tersebut diperlukan untuk membangun sistem pelayanan informasi sebagaimana diamanatkan UU. KPU periode sebelumnya telah melahirkan dua aturan terkait implementasi UU KIP ini, yaitu Standar Prosedur Operasional Pelayanan Data dan Informasi, serta PKPU No. 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Uji akses IPC membuktikan, dua aturan ini, tidak berjalan dengan efektif di KPU RI.
KPU di Daerah pun, setali tiga uang. Meski ada anggaran pengembangan PPID, namun dari 4 daerah yang diteliti IPC yaitu Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Aceh, tak satu pun yang memiliki PPID. Lalu kemana uangnya? Entah! Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dinilai sukses mensosialisasikan tahapan pemilu, tetapi sebagai badan publik, sungguh KPU, sejatinya masih tertutup. Indikasinya sederhana, mintalah informasi soal anggaran dan logistik kesekretariatan KPU atau lihatlah website KPU, adakah info tersebut?
Jika janji para komisioner KPU, untuk menjadi lembaga terbuka sukar terwujud, karena kesibukan pemilu, semoga pasca putusan MK nanti, mereka sempat berbenah diri. Membenahi sistem di internal, sesungguhnya bagian dari tanggung jawab pimpinan KPU.

oleh Parliamentary Center | Jul 8, 2014 | Editorial
Ada 3 momentum yang menarik perhatian publik, beberapa hari ini. Ramadhan, pilpres, dan piala dunia. Pilihan publik terhadap awal Ramadhan dan tim favorit piala dunia, berbeda-beda. Tapi, coba lihat di dunia nyata dan maya, efek perbedaan itu, kalah dahsyat dari efek perbedaan pilihan terhadap capres-cawapres.
Sepanjang sejarah Indonesia, inilah Pilpres yang paling banyak menyedot emosi publik. Berbagai kalangan, ikut ambil bagian membangun opini. Ratusan komunitas terbentuk untuk menyatakan dukungan atau penolakan, pada calon tertentu. Sejumlah aktivis NGO tak henti berdemonstrasi dan kampanye menolak salah satu calon. Bahkan, sekelompok ulama di Jawa Barat mengeluarkan fatwa haram memilih salah satu calon. Begitulah, mulai dari kiyai hingga artis, mendadak peduli dan jadi brand ambassador.
Di dunia maya tak kalah seru. Masih ingat blunder Wimar Witoelar, hingga ia harus minta maaf ke organisasi Muhammadiyah. Pun jangan heran jika media sosial Anda, tiba-tiba di-unfriend atau di-unfollow, bahkan oleh teman karib sendiri. Karena beda pilihankah? Mungkin. Atau barangkali kampanye Anda yang membuat mereka bosan. Yup, isinya, itu lagi, itu lagi.
Di tengah gemuruh perbincangan itu, sayangnya program ril para Capres-Cawapres tak banyak dibiicarakan khalayak. “2 juta ha sawah baru” Prabowo atau “Kartu Sehat” Jokowi, sepi perdebatan. Apalagi, tentang konsep mereka terhadap reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, keterbukaan informasi, dan konsep lainnya, hanya jadi konsumsi sedikit aktivis NGO.
Dalam membangun negeri ini, setidaknya lima tahun ke depan. Bukankah, konsep-konsep itulah yang dibutuhkan? Nah, masih ada waktu untuk berpikir lebih jernih, sebelum menentukan pilihan kita, besok. Selamat memilih Presiden baru.

oleh Parliamentary Center | Jun 3, 2014 | Editorial
Sungguh, kita membutuhkan Presiden yang memiliki visi mewujudkan pemerintahan yang transparan. Selain hak, informasi publik akan mempermudah terwujudnya pemenuhan hak-hak ekosob warga Negara. Asumsinya, dengan baiknya ketersediaan dan pelayanan informasi publik, warga akan terpicu untuk mendapatkan haknya. Di sisi lain, birokrasi relatif berhati-hati dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, karena publik punya informasi memadai terhadap semua proses tersebut.
Lalu pertanyaannya, dari dua pilihan yang kini disajikan untuk publik, siapa yang lebih layak? Memang jika mengacu pada partai-partai yang mengusung mereka, ah, nyaris pupuslah harapan itu. Tak ada partai yang punya keseriusan mendorong keterbukaan. Sejatinya, UU KIP sendiri produk mereka yang disokong masyarakat sipil, namun urusan implementasi, sama sekali jauh panggang dari api. Padahal di berbagai negara demokratis, tak ada perdebatan bahwa partai politik adalah badan publik, yang juga wajib terbuka.
Harapan itu, kini kita tumpukan pada personal capres-cawapres. Sejauhmana integritas dan rekam jejak mereka pada pemerintahan yang terbuka. Siapapun yang terpilih, publik perlu mendorong agar “Keterbukaan Informasi Publik” menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi pemerintah baru. Kita akan saksikan, apakah presiden baru cukup punya nyali untuk menerapkan UU KIP pada institusi kepresidenan. Jika tidak, sulit berharap ia jadi contoh bagi pemerintahan di level berikutnya. Jika demikian, apa bedanya kita dengan Thailand, negara yang punya UU KIP, tapi raja dan keluarnya tak dapat tersentuh oleh UU tersebut.
Itulah mengapa Official Information Act (UU KIP) di Negeri Gajah Putih itu, hanya mengasilkan seorang Sumalee, dialah menginspirasi lahirnya UU KIP di Thailand, tahun 1997, dia pula menjadi contoh baik implementasi UU, tapi… kok selalu dia, ya hingga kini selalu dia. Dia lagi, lagi. Kita khawatir dengan nasib UU KIP di tangan presiden baru mendatang, bisa jadi regulasi ini menuju gejala “thailandisasi”.
Begitulah kira-kira, jika UU KIP dilahirkan lalu dibiarkan, bahkan pemimpinnya sendiri tak dapat tersentuh, ia tidak akan membawa dampak signifikan bagi perbaikan kehidupan warga. Sementara di sisi lain, betapa seriusnya kelompok masyarakat sipil melakukan peningkatan kapasitas warga, melakukan uji akses, sengketa informasi, pendampingan badan publik, dan berbagai upaya lain untuk mendorong keterbukaan. Sebuah tujuan, yang sejatinya mudah bagi Presiden, jika ia mau turun langsung menggunakan kuasa kerongkongan dan telunjuknya di hadapan badan publik, yang masih saja bebal, hingga kini. Ya, hingga 6 tahun, sejak UU tersebut disahkan!

oleh Parliamentary Center | Des 3, 2013 | Editorial
Editorial.
Entah, pepatah atau peribahasa apa yang pas untuk menggambarkan perilaku seperti ini; membuat aturan lalu mengkhianatinya sendiri. Kira-kira, begitulah gambaran bagi sebagian besar partai politik saat ini. Tapi sudahlah, berhalus-halus kata lewat aneka majas ala bahasa Indonesia, kadang mengalpakan kita ada makna sesungguhnya. Langsung saja, jika mengacu pada terminologi hadits, maka “munafik” adalah istilah yang tepat untuk perilaku di atas.
Nah, mari masuk pada konteksnya. Lima tahun lalu, fraksi-fraksi yang merupakan kepajangan partai politik di parlemen berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dua tahun kemudian, UU ini diberlakukan. Mari baca di pasal 15. Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah: a. asas dan tujuan; b. program umum dan kegiatan partai politik; c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. mekanisme pengambilan keputusan partai; f. keputusan partai: hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.
Apa yang terjadi? Sejak UU ini diberlakukan pada 2010, nyaris tak ada satu pun partai politik di tingkat nasional maupun daerah yang mengimplementasikannya. Bahkan, diminta pun, tidak mereka beri. Di tingkat pusat, ada Indonesian Corruption Watch yang melakukan uji akses pada 9 partai politik, pada 2012 lalu. Di daerah, ada Garut Governance Watch (Jabar), Fitra NTB, Pokja 30 (Kalimantan Timur), Masyarakat Transparansi Aceh, dan berbagai organisasi lainnya melakukan uji akses. Tapi hasilnya sama, informasi itu tak dibuka. Jika pun ada yang membuka, melalui proses yang berbelit-belit hingga sengketa di Komisi Informasi.
Sekarang, mari kita lihat UU lain yang disahkan oleh fraksi-fraksi -sekali lagi- yang merupakan kepanjangan partai politik di parlemen. Dua tahun lalu, UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik mereka lahirkan. Dalam Pasal 39, disebutkan (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas. Adakah yang melakukannya, khususnya pada poin: diumumkan secara periodik. Lagi-lagi jawabnya sama. Tak! Tak ada.
Jika pada UU yang mereka buat sendiri, berani dikhianati, jangan heran sikap seperti itu diberlakukan pula pada rakyat yang memilih mereka. Ironis! Hari ini, memang tak ada partai yang mengaku anti-transparansi. Tapi tanpa implementasi, pernyataan itu hanya retorika politik.

oleh Parliamentary Center | Nov 26, 2013 | Editorial
Hak atas informasi atau hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan infromasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi di dalam negara demokrasi memegang peranan penting dalam membangun partisipasi warga dan mendorong pemerintahan yang demokratis, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.
Sayangnya hingga kini, lembaga publik di Indonesia masih identik dengan ketertutupan. Tidak terkecuali lembaga publik yang menangani sektor migrasi ketanagakerjaan. Buruh Migran Indonesia (BMI) yang sering disebut sebagai “pahlawan devisa” hingga saat ini masih mengalami persoalan pelik seputar ketersediaan informasi. Akibatnya, banyak BMI yang dirugikan atas ketidaktransparanan ini. Demikian yang terungkap dalam Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Di Sektor Migrasi Ketenagakerjaan 2013.
Laporan yang disusun atas kerjasama Infest, Pusat Sumber Daya Buruh Migran, MediaLink, dan Yayasan TiFA tersebut mengungkapkan beberapa kasus yang terjadi akibat minimnya informasi ketenagakerjaan adalah daftar pengguna jasa bermasalah. Padahal UU Nomor 39 tahun 2004 mewajibkan pihak KJRI secara berkala menginformasikan daftar pengguna jasa bermasalah dalam daftar hitam. Kasus lain adalah persoalan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN). Beberapa serikat buruh Migran seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Pusat Sumber Daya Buruh Migran serta jaringan kerja BMI menyatakan adanaya kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan pelanggaran pada bidang ini.
Informasi terkait pengawasan pihak swasta yang terkait dengan penempatan BMI, seperti PPTKIS dan konsorsium asuransi juga sangat sulit ditemukan dalam berbagai saluran informasi. Hal ini tentu akan memperbesar kemungkinan BMI menjadi objek pelanggaran hukum. Janji BNP2TKI yang menerapkan sistem daftar hitam (black list) PPTKIS hingga saat ini pun tak kunjung membuahkan hasil.
Persoalan lain adalah informasi yang dikeluarkan oleh masing-masing badan publik yang kontradiktif antara satu dan yang lain. Secara umum, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dan BNP2TKI adalah dua lembaga yang secara spesfik mengurusi bidang tersebut. Di daerah, kedua lembaga tersebut memiliki turunan serupa yang mengurusi bidang ini, seperti Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)di Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja. Kementrian Luar Negeri (Kemlu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian Sosial (Kemsos) dan kepolisian adalah deret lembaga publik yang turut mengurusi isu ini. Ditingkat daerah dari 18 BP3TKI hanya 3 yang mempunyai website.
Oleh sebab itu, paling tidak ada dua persoalan besar dalam persoalan buruh migran. Pertama, adalah ketersediaan informasi oleh lembaga publik yang bertanggung jawab. BNP2TKI, Kemenakertrans, dan Kemenlu harus memperkuat koordinasi untuk memperkuat informasi yang dibutuhkan oleh BMI. Kedua, Akurasi Informasi yang disampaikan harus benar-benar valid supaya tidak terjadi kontradiksi informasi.
Dengan mengupayakan implementasi UU KIP di sektor buruh migran, diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga publik terkait. Serta meningkatkan kontrol publik terhadap kinerja lembaga publik dalam bidang buruh migran.